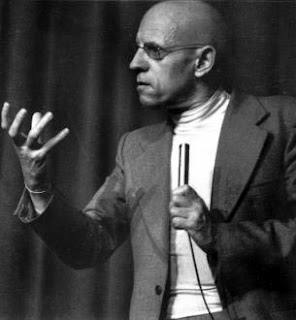Ketika ngobrol panjang dengan Livia van Helvoort, tempo hari di hotel Tugu, Malang, saya sedikit bisa memahami mengapa Geert Wilders memiliki perspektif demikian mengerikan mengenai Islam. Tentu saya tidak bisa membenarkan pemahaman cupet politisi Belanda itu, yang menganggap muslim di mana saja di kolong langit ini sama saja.
Cuma yang menarik, dari cerita Livia juga Henk Nijhof , film Fitna bikinan Wilders sebetulnya kontekstual dengan dilematisnya pemerintah (juga warga) Belanda sekarang, berhadapan dengan imigran dari Maroko dan Turki yang hampir semuanya muslim.
Dalam beberapa tahun ini, Livia menyebut problem sebagian orang-orang muslim sebagai masalah inti negaranya. Bayangkan, masalah utama !. Kelakuan mereka dalam keseharian tidak saja mencoreng dan mengawut-awutkan wajah Islam di mata orang Eropa, namun juga melukai nilai kemanusiaan.
Saya sebagai muslim sungguh miris mendengar pengalaman-pengalaman Office Manager di Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) itu.
Di Belanda, orang-orang Maroko misalnya, tinggal di pemukiman-pemukiman miskin dan rentan kriminalitas. Dari data pemerintah hampir 70 % tindak kejahatan di Belanda, dilakukan oleh mereka.
Tindakan urakan meneriaki setiap perempuan Belanda yang melintas di depan mereka dengan sebutan slut atau hooker (pelacur), dan homo, bagi lelaki yang semisal berkuncir, sungguhlah memalukan.
Belum lagi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Kebanyakan lelaki Maroko dan Turki di Belanda tidak segan-segan menyiksa istri atau pacar-pacarnya. Laporannya sering masuk ke kantor polisi. Banyak juga kasus yang menceritakan tentang, suami yang seenaknya saja meninggalkan istrinya yang sedang hamil dan mengambil si anak ketika jabang bayi mulai tumbuh.
Dengan reputasi seperti itu, perempuan-perempuan lokal oleh karenanya menjauhi berkencan dengan lelaki-lelaki Maroko atau Turki.
Banyak juga masjid yang terpaksa ditutup karena mengajarkan jamaahnya menjadi ekstremis. Yang paling dekat, pengeboman kereta bawah tanah London tahun 2004, menjadi momok menakutkan dan meninggalkan kecurigaan akut pada muslim bagi negara-negara Eropa barat, tak terkecuali Belanda.
Polisi juga tidak bisa bertindak terlampau keras. Seperti banyak negara Eropa barat lain, Belanda sangat menjunjung tinggi isu-isu hak asasi manusia. Jika agak strength menangkapi orang-orang Arab itu, salah-salah bisa dituduh diskriminatif.
Saya, mas Hesti juga Epy dan Athok yang menemani Livia dan Henk makan malam tempo hari, merasa berkewajiban bercerita bahwa wajah Islam dibelahan dunia lain termasuk Indonesia tidak melulu seperti itu.
Islam, sebagaimana dicerminkan Muhammad Rasulullah sejatinya adalah agama yang lembut, damai, adem dan sangat toleran terhadap perbedaan. Maka tidak hanya ada satu surga sebetulnya yang bisa kita gapai kelak, kita pun sebenarnya dituntut untuk menciptakan surga di dunia ini. Tanpa ada perang, kekerasan, saling bunuh dan kebencian.
Di akhir makan malam, Livia yang tidak pergi ke gereja lagi itu, menyalami saya dengan erat, berterimakasih atas perspektif barunya tentang Islam. Ia juga mencium pipi saya dan kawan-kawan tiga kali, tanda persahabatan hangat dalam tradisi Belanda.
Saya-pun mendapatkan pelajaran baru lewat sosok Livia yang ramah dan energik. Serta melalui Henk, Presiden partai GroenLinks (Green Left), yang sangat kalem dan kebapakan itu. Mereka berdua setidaknya juga meruntuhkan stigma saya selama ini pada imagi orang Belanda yang kasar dan keras.
Read More......